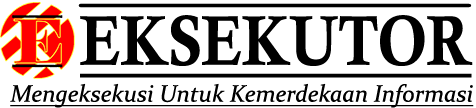SEOUL — Proses hukum terhadap mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memasuki babak krusial setelah jaksa menuntut hukuman mati atas dakwaan pemberontakan yang berkaitan dengan deklarasi darurat militer pada akhir 2024. Tuntutan tersebut menandai salah satu kasus paling serius dalam sejarah hukum dan demokrasi Korea Selatan, sekaligus menjadi preseden penting bagi akuntabilitas kekuasaan eksekutif di negara itu.
Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Selasa (13/01/2026), jaksa khusus menegaskan bahwa Yoon bukan sekadar pengambil keputusan situasional, melainkan sosok yang dinilai berperan sentral dalam perencanaan langkah yang mereka sebut sebagai upaya pemberontakan. Jaksa bahkan menyebut Yoon sebagai “dalang pemberontakan” dan mengungkapkan hasil penyelidikan yang menyimpulkan bahwa skema tersebut telah dirancang sejak 2023, jauh sebelum deklarasi darurat militer diumumkan.
Menurut jaksa, bukti-bukti yang dihimpun menunjukkan adanya rencana sistematis untuk mengambil alih fungsi-fungsi negara di luar mekanisme konstitusional. Tuduhan ini memperkuat pandangan bahwa deklarasi darurat militer bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari strategi yang telah disusun sebelumnya.
Yoon Suk Yeol, yang kini berusia 65 tahun, menolak seluruh tuduhan tersebut. Ia tetap bersikukuh bahwa langkahnya berada dalam koridor kewenangan presiden. Ia berdalih, keputusan tersebut diambil di tengah kebuntuan politik yang berkepanjangan di parlemen serta dugaan ancaman keamanan nasional. Yoon juga menyinggung adanya apa yang ia sebut sebagai “pemberontakan” yang direncanakan oleh kekuatan pro-Pyongyang di dalam oposisi politik, sebagaimana dilaporkan RT.
Namun, deklarasi darurat militer pada Desember 2024 justru memicu reaksi keras dari publik. Ribuan warga turun ke jalan dalam aksi protes, sementara Majelis Nasional bergerak cepat membatalkan keputusan tersebut hanya dalam hitungan jam. Parlemen secara bulat menilai langkah itu melampaui batas kewenangan eksekutif dan mengancam prinsip demokrasi.
Peristiwa tersebut menjadi sangat sensitif karena merupakan penggunaan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1980. Ratusan personel bersenjata kala itu dikerahkan ke sejumlah institusi vital negara, termasuk Majelis Nasional. Langkah ini dipersepsikan banyak pihak sebagai upaya untuk menghambat fungsi legislatif dan mendahului kewenangan parlemen.
Tekanan publik yang masif berujung pada krisis politik berkepanjangan. Yoon ditangkap pada Januari 2025, kemudian Mahkamah Konstitusi secara resmi mencopotnya dari jabatan presiden pada April tahun yang sama. Ia tercatat sebagai presiden pertama Korea Selatan yang ditahan dan menghadapi tuntutan pidana saat masih menjabat.
Secara hukum, tuntutan mati dimungkinkan dalam kasus pemberontakan. Namun, fakta bahwa Korea Selatan belum melakukan eksekusi sejak 1997 membuat banyak pengamat menilai hukuman penjara seumur hidup sebagai skenario yang lebih realistis. Mahkamah dijadwalkan membacakan putusan pada Februari mendatang.
Dampak politik dari pencopotan Yoon juga signifikan. Pemilihan presiden mendadak yang digelar setelahnya dimenangkan oleh Lee Jae-myung. Pemerintahan baru kemudian mengubah arah kebijakan luar negeri dan keamanan, termasuk mengambil langkah normalisasi hubungan dengan Korea Utara, seperti menghentikan siaran propaganda di wilayah perbatasan. Kebijakan ini menjadi kontras tajam dengan pendekatan garis keras yang sebelumnya diterapkan Yoon. []
Diyan Febriana Citra.