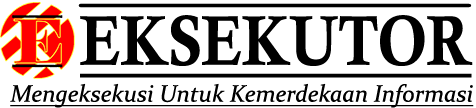JAKARTA – Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memantik keprihatinan luas dan menjadi sorotan serius pemerintah pusat. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai musibah kemanusiaan, tetapi juga cermin persoalan sosial yang lebih dalam terkait akses pendidikan, kemiskinan, dan lemahnya jaring pengaman sosial di tingkat masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kasus tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen bangsa. Ia menilai tragedi ini tidak boleh dipahami sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat.
“Ya, ini harus menjadi cambuk ya,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (03/02/2026) malam.
Menurut Cak Imin, peristiwa ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar yang harus diperbaiki dalam sistem perlindungan sosial. Ia menekankan pentingnya membangun kepekaan sosial di lingkungan sekitar agar masyarakat lebih terbuka untuk saling menolong dan peka terhadap kondisi sesama.
“Kita juga harus cari akar masalah frustrasi sosial itu sudah sejauh mana,” katanya.
Tragedi ini bermula dari kisah pilu seorang anak yang mengakhiri hidupnya setelah tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000. Korban meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, MGT (47), yang menjadi bukti betapa berat tekanan psikologis yang ia rasakan. Surat tersebut menjadi simbol luka sosial yang lebih luas, menggambarkan keterbatasan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin di wilayah pedesaan.
Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.
Surat tersebut menyentuh hati banyak pihak dan memunculkan diskusi publik tentang pentingnya kesehatan mental anak, terutama yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi rentan. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana tekanan kecil secara materi, seperti kebutuhan alat tulis, dapat berubah menjadi beban besar secara psikologis ketika anak tidak memiliki ruang aman untuk bercerita dan meminta bantuan.
Korban diketahui tinggal bersama neneknya. Sementara itu, ibundanya yang merupakan orang tua tunggal harus bekerja sebagai petani dan pekerja serabutan untuk menghidupi lima orang anak. Kondisi ini mencerminkan realitas banyak keluarga prasejahtera di daerah, yang hidup dalam keterbatasan namun tetap berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Dari perspektif kebijakan publik, tragedi ini memperkuat urgensi penguatan program perlindungan sosial, terutama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin. Akses pendidikan gratis saja dinilai belum cukup jika kebutuhan dasar pendukung pendidikan, seperti buku, alat tulis, dan dukungan psikososial, belum sepenuhnya terjamin.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari warga paling rentan. Anak-anak seharusnya menjadi kelompok yang paling dilindungi, bukan justru menjadi korban dari ketimpangan sosial.
Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat, publik berharap tragedi ini tidak berhenti sebagai berita duka, tetapi menjadi momentum perbaikan sistem sosial secara nyata. Tragedi di Ngada diharapkan menjadi refleksi bersama bahwa kemiskinan, keterbatasan akses, dan minimnya empati sosial dapat menciptakan luka yang jauh lebih besar dari sekadar angka statistik kemiskinan. []
Diyan Febriana Citra.