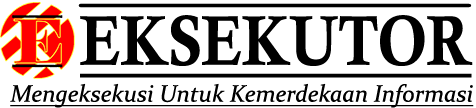SEJAK diberlakukannya otonomi daerah (otda) dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nuansa dan kehidupan demokrasi di negeri yang dijuluki zamrud khatulistiwa ini semakin dinamis.
Pemilihan kepala daerah oleh rakyat bagaikan magnet yang menyedot energi seluruh elemen masyarakat terutama para pelaku politik. Semua pihak yang merasa dirinya adalah anak bangsa dan merupakan bagian dari warga negara Indonesia berhak untuk ambil bagian dalam sistem demokrasi itu.
Dinamika ini bahkan telah menciptakan suatu tatanan demokrasi tanpa ujung akhir bahkan sampai detik ini.
15 tahun berlalu sejak otonomi daerah dicanangkan, bangsa ini masih tetap berkutat dalam perdebatan mencari sistem yang benar-benar tepat dan cocok bagi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terutama proses dan tatacara pemilihan kepala daerah.
Kendatipun dalam proses menuju sistem yang tepat ini telah menelan banyak ‘korban’ sebagai tumbal dari pencarian jati diri otda, namun dinamika ini tak pernah surut dan akan terus berlangsung entah kapan berakhir.
Saat ini, suhu politik di daerah daerah di Indonesia semakin meningkat karena proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung di berbagai daerah kabupaten/kota mengingat masa kepemimpinan bupati/walikota segera berakhir.
Partai politik (parpol) menjelma menjadi peri cantik dari kahyangan, didekati, dibujuk dan dirayu untuk memberikan ‘panah asmara’ berupa dukungan kepada figur tertentu yang merasa mampu menjadi pemimpin di daerahnya .
Syarat dukungan 20 persen bagi calon kepala daerah membuat para kandidat bergegas untuk mendapatkan partai yang mau memberikan dukungannya dan pada akhirnya terjadilah transaksi dengan tarif yang mencengangkan namun tak pernah sepi peminat, walaupun di sisi lain masih ada syarat dukungan 5 persen dari masyarakat yang tidak memasang harga.
Para penawar lebih cenderung mengejar dukungan parpol dari pada harus mencari dukungan rakyat yang dibuktikan dengan menyerahkan kartu identitas berpuluh-puluh puluh ribu. Namun di tengah- tengah dinamika kekinian proses Pilkada itu kembali lagi saya dikagetkan oleh pengamatan pribadi bahwa ada anomali yang bakal terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Daerah ini memang unik dan menyimpan banyak misteri serta ketidak laziman, terutama menyangkut kehidupan demokrasi dan politik. Selalu ada yang baru di negeri ini tatkala memasuki saat saat proses demokrasi dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden bahkan Pilkada.
Dan kenyataan ini membuat rasio dan nalar saya tergerak untuk mengutak-atik hurup dan angka angka untuk dituliskan .
MISTERI SELASA
Rita Widyasari dengan pasangannya Ghufron Yusuf, akan berakhir dari posisinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar pada 30 Juni 2015, sesaat setelah jarum jam berdetak melangkah sedetik memasuki hari Selasa. Hari itu sebenarnya istimewa, sebab di hari itu waktu bumi akan ditambahkan satu detik akibat melambatnya rotasi bumi 1/2000 detik setiap hari.
Maka untuk menyamakan ketepatan waktu antara rotasi bumi itu dengan jam atom yang dipakai sebagai patokan penetapan waktu di bumi, harus dilakukan penyesuaian dan tahun ini terjadi pada 30 Juni 2015. Inilah yang disebut detik kabisat, dan untuk ke 26 kalinya sejak tahun 1972, penambahan ini dilakukan pada kalender kita.
Meskipun tidak berpengaruh pada kehidupan manusia, tapi bisa menjadi ‘detik kiamat internet’ dalam skala kecil seperti terjadi pada tahun 2012 lalu dan sempat mengganggu beberapa penerbangan di dunia.
Selama detik kabisat ini jam komputer tetap bergerak 60 detik dan menganggap penambahan satu detik sebagai langkah mundur dan berakibat sistem tidak bisa melakukan pengenalan pada dua detik sehingga mesin komputer akan menganggap itu sebagai kesalahan sistem dan CPU akan mengalami beban berat.
ANOMALI DI KUKAR
Mari kita lewatkan ‘tikungan’ detik kabisat itu dan mulai dengan analisa anomali pilkada di Kukar.
Silang sengkarut penetapan waktu Pilkada maupun syarat – syarat keikutsertaan para calon pemimpin di daerah daerah itu memang masih berlangsung, baik pada proses politik di Senayan maupun Mahkamah konstitusi berupa proses uji materi (yudicial review) masih tetap berlangsung, tapi ada baiknya kita kesampingkan hal itu untuk menghemat energi pikiran.
Ketentuan yang mensyaratkan dukungan utuh 20 persen dari parpol yang duduk di parlemen daerah, memastikan bahwa hanya partai Golkar yang bisa secara utuh mengusung calon bupati. Itu karena perolehan 19 kursi di DPRD Kukar sudah jauh melampaui syarat dukungan yang secara matematis berjumlah 9 orang keterwakilan utuh di DPRD.
Sementara dari kursi yang tersisa sebanyak 26 orang, tidak ada satupun parpol yang secara utuh memiliki 9 wakilnya. Sebab itu harus dilakukan proses koalisi dan pastinya hanya ada peluang dan kemungkinan sebanyak dua calon lagi. Artinya, hanya ada maksimal tiga calon yang bisa diusung dari partai politik penguasa parlemen di Kukar.
Gambaran aritmatikanya, jika sisa kursi selain partai Golkar sebanyak 26 kursi, dengan syarat dukungan 9 kursi dikali 2 sebanyak 18 kursi, maka sisanya sebanyak 8 kursi. Sementara parpol-parpol pemilik kursi di parlemen selain Golkar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 6 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindera) 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi dan Partai Bulan Bintang sebanyak 1 kursi.
Dan jika mengamati komunikasi politik yang terbangun dalam relasi oposisi-koalisi yang ada di DPRD Kukar maka hanyalah PDIP. Maka, menurut hemat saya, melalui analisa dari pengamatan secara umum berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, dengan kemampuan komunikasi politik yang lugas maka partai Golkar bisa mendapatkan dukungan dari kompatriot yang tergabung dalam koalisi di DPRD.
Apalagi jika dilihat dari komposisi secara nasional, relasi Koalisi Merah Putih (KMP) – Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka yang bisa berkoalisi mengusung calon selain Rita Widyasari hanyalah koalisi PDIP- HANURA dengan 10 kursi .
Kalkulasi tersebut pada akhirnya hanya memunculkan dua bakal calon dari parpol atau setidak-tidaknya akan bertambah calon dari dukungan masyarakat sebagai calon independen.
Akan tetapi saya meyakini, bila tidak terjadi intervensi kepada parpol-parpol yang berhak mengusung calon, maka bukan tidak mungkin semua parpol koalisi di DPRD akan mengusung Bunda Rita—sapaan akrab Rita Widyasari, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kukar—sehingga PDIP tidak bisa mendapatkan ‘sahabat’ untuk memenuhi syarat ketercukupan mengusung calon Bupati, dengan demikian maka peluang yang tersisa hanyalah dari calon independen yang maksimal 1 orang.
Kondisi inilah yang saya sebutkan sebagai anomali tatkala terjadi ketika menjelang masa pencalonan, tidak ada satupun calon yang bisa bertanding melawan ‘ Bunda’.
Para pendukung dan tim sukses sang incumbent ini tidak boleh gegabah dengan menafikan kondisi yang ada, sebab untuk mencari dukungan independen harus dipersiapkan dari sekarang sedangkan dukungan parpol sudah tidak bisa dirombak lagi, maka hal ini bisa membatalkan proses Pilkada.
Mengumpulkan dukungan konkrit untuk calon independen dengan bukti kartu identitas diri bukanlah perkara mudah, mengingat akan diverifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan bukan tidak mungkin masyarakat sengaja atau lupa bahwa secara administratif namanya tercatat sebagai anggota parpol, mengingat proses rekrutmen anggota parpol kala pemilihan legislatif beberapa waktu lalu, terkesan dilakukan secara sporadis dan terburu buru. Oleh karena itu, kemungkinan seperti gambaran di atas bisa saja terjadi dalam proses dan tahapan Pilkada Kukar.
Karena itu sembari menanti datangnya ‘keriuhan demokrasi’ yang bernama Pilkada, mari kita nantikan ujung akhir analisa tentang anomali itu dalam semangat untuk membangun bumi etam tercinta. Dan jangan lupa untuk memberikan suara pilihan melalui pertimbangan rasional dengan membandingkan desa-desa tempat tinggalmu sekian tahun lalu dan kenyataan pada masa sekarang. Ayo bersatu Bena Benua Etam! ***