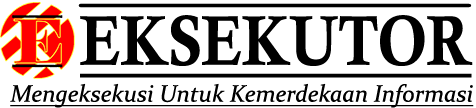JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini menerima gaji hingga Rp230 juta per bulan atau Rp2,7 miliar per tahun, jauh di atas profesi sektor publik lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan profesionalisme legislatif, karena publik menilai kinerja DPR belum sebanding dengan remunerasi yang diterima.
Profesionalisasi legislatif bukan hal baru. Sejak 1971 di Inggris, anggota parlemen menerima gaji dari negara agar dapat bekerja penuh waktu tanpa harus menanggung pekerjaan lain. Sistem ini juga memisahkan gaji pokok dari tunjangan bisnis parlemen, seperti kendaraan, sekretariat, dan dana daerah pemilihan (Dapil). Profesionalisme legislator tidak hanya diukur dari undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga proses penyerapan aspirasi publik, transparansi dokumen, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban.
Di Indonesia, upaya profesionalisasi legislasi sudah dimulai sejak era DPR Gotong Royong (1961), ketika gaji dan tunjangan anggota DPR tergantung pada kehadiran rapat. Namun, regulasi berikutnya sejak 1974 hingga 2015 tidak lagi menetapkan kehadiran sebagai syarat penerimaan gaji, sehingga muncul risiko konflik kepentingan. Sejak Reformasi 1998, DPR memiliki otonomi lebih besar untuk menentukan hak keuangan dan administratifnya sendiri, sebagaimana diatur dalam UU MD3 (2009 dan 2014).
Publik menyoroti dua masalah utama. Pertama, remunerasi tinggi harus dibarengi profesionalisme tinggi, termasuk representasi publik, transparansi rapat, revisi anggaran berbasis aspirasi, dan laporan reses yang terstruktur. Kedua, DPR belum mampu menjelaskan basis penentuan gaji dan tunjangan, sehingga publik sering menilai remunerasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau partai.
Untuk mengatasi konflik kepentingan dan meningkatkan profesionalisme legislatif, dibutuhkan terobosan berupa pembentukan panel independen. Panel ini bertugas meninjau standar profesionalisme parlemen, menetapkan gaji, tunjangan, dan biaya bisnis parlemen secara transparan dan proporsional. Contohnya, Inggris memiliki Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), sementara Selandia Baru memiliki Remuneration Authority yang menetapkan remunerasi parlemen berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan perbandingan dengan sektor lain.
Di era keterbukaan informasi, publikasi gaji, tunjangan, dan penggunaan biaya legislatif menjadi penting. Dengan panel independen, DPR dapat membangun kembali kepercayaan publik dan menepis kecurigaan terkait remunerasi, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap profesionalisasi legislatif.[]
Putri Aulia Maharani