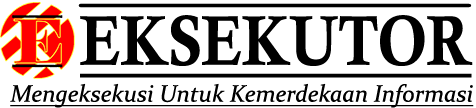PARLEMENTARIA – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Balikpapan terus menuai reaksi keras. Isu ini tidak lagi sekadar soal angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap cara pemerintah daerah mengambil kebijakan fiskal.
Keresahan warga mencuat setelah seorang penduduk Balikpapan mengunggah bukti tagihan pajak di media sosial. Dalam unggahannya, ia menyoroti lonjakan PBB miliknya yang naik tajam dari Rp300 ribu menjadi Rp9,5 juta hanya dalam setahun. Informasi itu segera menyebar luas dan memantik diskusi hangat, terutama karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi, kemudian turun langsung menelusuri kebenaran kasus tersebut. Dari hasil pengecekan, ia justru menemukan fakta lain yang lebih mencengangkan. “Awalnya kabar ini mencuat di media sosial, lalu kami cek di lapangan. Ada kasus dari Rp500 ribu menjadi Rp12,9 juta. Itu sekitar 2.500 persen kenaikannya, ini sangat tidak masuk akal,” tegas Nurhadi, Kamis (21/08/2025).
Fenomena lonjakan tarif PBB ternyata bukan hanya terjadi di Balikpapan. Beberapa daerah lain di Indonesia pernah mengalami gejolak serupa. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kenaikan hingga 250 persen sempat memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang bahkan berujung pada desakan pemakzulan bupati. Situasi tak jauh berbeda terjadi di Jombang dan Cirebon, di mana tarif naik hingga 1.000 persen. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, kenaikan rata-rata 65 persen juga memicu aksi protes.
Di Kalimantan Timur sendiri, Samarinda juga menaikkan PBB sebesar 25 persen. Namun, pemerintah kota setempat masih memberi keringanan berupa diskon, sehingga gejolak publik relatif bisa diredam. Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Nurhadi. “Kita tidak mau ada kejadian seperti di Pati. Jangan sampai Balikpapan mengalami hal yang sama. Pemerintah kota harus responsif, dan DPRD Balikpapan harus cepat tanggap,” ujarnya.
Hingga kini, DPRD Kaltim melalui Komisi II masih menunggu penjelasan resmi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Balikpapan terkait dasar perhitungan kenaikan tarif. Menurut Nurhadi, transparansi dalam perumusan kebijakan adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. “Kami masih menunggu penjelasan. Jangan sampai rakyat dikorbankan karena kesalahan perhitungan atau kebijakan yang tidak sensitif,” tambahnya.
Pandangan kritis juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai kebijakan menaikkan PBB secara drastis adalah langkah instan yang terlalu mengedepankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini cara paling gampang dan tradisional. Pemerintah perlu strategi yang lebih kreatif untuk meningkatkan PAD, bukan langsung membebani masyarakat lewat pajak,” jelasnya.
Menurut Purwadi, pemerintah daerah seharusnya lebih inovatif dalam menggali potensi lokal. Pariwisata, sektor investasi, serta perbaikan tata kelola retribusi daerah dinilai masih menyimpan ruang besar untuk dikembangkan. “Jika hanya mengandalkan kenaikan pajak, pemerintah akan kehilangan simpati publik. Padahal, pajak seharusnya dilihat sebagai kontribusi sukarela untuk pembangunan, bukan beban yang menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Secara yuridis, PBB memang memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985. Regulasi tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan tarif. Namun, kewenangan itu bukan tanpa batas. Pemerintah tetap berkewajiban mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap stabilitas daerah.
Kasus Balikpapan ini menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi publik yang kurang memadai dapat memperburuk persepsi masyarakat. Transparansi data, keterbukaan mengenai dasar perhitungan tarif, serta dialog dengan warga seharusnya menjadi langkah awal sebelum kebijakan diberlakukan. Tanpa itu semua, setiap kenaikan akan dianggap sebagai keputusan sepihak yang mencederai rasa keadilan.
Lebih jauh, polemik ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak bisa hanya berorientasi pada peningkatan PAD. Legitimasi pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika kebijakan dianggap merugikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya penerimaan pajak, melainkan juga citra pemerintah dan stabilitas sosial.
Dengan kata lain, kasus ini seharusnya menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah, bukan hanya di Balikpapan, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kenaikan pajak, betapapun sah secara hukum, tidak boleh dilepaskan dari asas keadilan sosial dan prinsip keberpihakan pada rakyat. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna