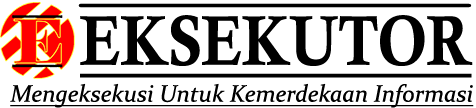Di tengah kampanye besar-besaran pemerintah soal hilirisasi sawit dan energi hijau, proyek biodiesel Jhonlin Group justru menyingkap sisi gelap transisi energi Indonesia. Di balik gemerlap investasi dan janji kemandirian energi, tersimpan kisah kriminalisasi warga, tumpang tindih izin, dan potensi pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi besar serta pejabat negara. Kasus Ratman dan warga Pulau Laut menunjukkan bahwa di negeri ini, suara rakyat bisa dipenjara, sementara pelanggaran korporasi justru dilindungi. Biodiesel yang digadang sebagai energi masa depan, kini menjadi cermin betapa “energi hijau” bisa tercipta dari praktik hukum yang kelabu.
KOTABARU – Di tengah kampanye pemerintah tentang hilirisasi sawit dan transisi energi hijau, bisnis biodiesel Jhonlin Group justru menyeret banyak pihak ke ranah hukum. Di balik megahnya proyek PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR), tersimpan persoalan hukum pidana yang menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap warga ketika berhadapan dengan korporasi besar. Alih-alih menjadi bagian dari masa depan energi bersih, rantai pasok perusahaan ini justru menimbulkan pertanyaan serius tentang penegakan hukum dan etika bisnis.
Salah satu kasus paling mencolok adalah yang menimpa Ratman, warga Pulau Laut yang tujuh tahun lalu harus mendekam di penjara hanya karena menyuarakan kritik terhadap PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), pemasok utama bahan baku biodiesel JARR. “Saya orasi minta bantuan Dewan (DPRD) agar menghentikan perusahaan. Omongan saya itu ada dasarnya. Karena masyarakat dizalimi. Perusahaan tidak ada komunikasi ke RT dan Desa,” ujarnya seperti dilansir dari Independen.id. Namun, kritik itu berujung pada jeratan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pada 28 November 2018, Ratman divonis dua bulan dua puluh hari penjara sebuah vonis yang menunjukkan bagaimana hukum pidana dapat digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk membungkam.
Kasus Ratman memperlihatkan bentuk kriminalisasi warga dalam konteks konflik agraria. Pasal pencemaran nama baik yang seharusnya melindungi reputasi individu digunakan untuk melindungi korporasi dari kritik publik. Dalam perspektif hukum pidana, praktik ini menjadi berbahaya karena menyalahi prinsip proporsionalitas: pidana digunakan sebagai alat represi, bukan koreksi sosial. Situasi ini semakin kompleks karena konflik yang melibatkan MSAM bukan sekadar perkara perdata, melainkan menyangkut hak atas tanah dan dugaan penyalahgunaan izin usaha perkebunan yang berpotensi masuk ranah pidana korporasi.
Imron, warga lain yang menjadi korban penggusuran, menuturkan kekecewaannya terhadap lemahnya perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. “Bagi kami, masyarakat biasa, petani, harusnya sertifikat (menjadi bukti kepemilikan) kuat. Tapi di lapangan, ternyata tidak berarti,” ujarnya. Sertifikat tanah hasil program PTSL bahkan yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo tidak mampu melawan kekuatan izin usaha perkebunan berskala besar. Ketika izin korporasi bertabrakan dengan hak milik warga, hukum justru berpihak pada pemodal.
Laporan investigasi IndonesiaLeaks memperkuat dugaan adanya pola sistematis kriminalisasi warga. Warga yang menolak menyerahkan lahan sering dihadapkan dengan aparat atau dijerat dengan UU ITE. Beberapa nama seperti Ansor dan Syahbudin alias Abah Putra menjadi contoh bagaimana pasal-pasal pidana disalahgunakan untuk kepentingan bisnis. “Kalau dari jalan hauling, saya dapat kurang dari Rp10 juta. Pembayaran dilakukan di Polsek. ‘Ada apa?’ dalam hatiku begitu,” ujar Ansor, yang heran mengapa transaksi ganti rugi dilakukan di kantor polisi, bukan di lembaga keuangan atau instansi resmi. Situasi ini menunjukkan campur tangan aparat dalam urusan sipil, yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang menurut hukum pidana administrasi.
Sementara itu, Syahbudin harus menjalani hukuman penjara 1 tahun 2 bulan karena unggahannya di media sosial yang diklaim “hoaks” tentang aktivitas MSAM. Laporan itu datang bukan dari perusahaan, tetapi dari anggota patroli siber bernama Askar. Dalam konteks hukum pidana, kasus ini menunjukkan perluasan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, di mana pasal karet UU ITE menjadi senjata efektif untuk menekan warga desa yang menuntut haknya.
Dari sisi korporasi, PT MSAM mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.553 hektare pada 2018. Namun, data Sawit Watch menunjukkan penguasaan riil mencapai 14.333 hektare selisih hampir 4.000 hektare yang belum jelas status hukumnya. Perbedaan angka ini membuka kemungkinan adanya pelanggaran pidana di bidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah atau Pasal 94 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kejanggalan makin mencolok ketika Inhutani II, BUMN pengelola hutan, menandatangani perjanjian kerja sama dengan MSAM pada 19 Juni 2017—hanya sebulan setelah perusahaan mencabut gugatan terhadap Kementerian Kehutanan. Perjanjian itu memberi hak kelola eksklusif bagi MSAM dengan imbal hasil 7,5 persen untuk Inhutani II. Ironisnya, izin HGU justru keluar sebelum kawasan hutan dilepaskan secara resmi. Dari perspektif hukum administrasi dan pidana lingkungan, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan proses perizinan atau persekongkolan dalam jabatan.
Lebih jauh, keterlibatan dua pejabat aktif dalam kabinet Prabowo-Gibran, yakni Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, yang tercatat pernah menjadi pemegang saham MSAM, menambah kompleksitas hukum kasus ini. “Waduh enggak tahu saya, MSAM itu apa ya?” ujar Dody ketika dikonfirmasi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan etis sekaligus yuridis: apakah terdapat potensi pelanggaran Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
MSAM dikendalikan oleh PT Eshan Agro Sentosa (EAS), anak usaha Jhonlin Group yang juga pemegang saham mayoritas JARR. Hubungan ini menandakan adanya struktur korporasi vertikal yang bisa dikenai prinsip vicarious liability dalam hukum pidana korporasi. Jika terbukti ada pelanggaran di MSAM, maka entitas induk Jhonlin Group dan penerima manfaat ekonomi, termasuk JARR, seharusnya tidak luput dari tanggung jawab hukum.
Pasokan minyak sawit mentah (CPO) dari MSAM ke JARR mencapai Rp393 miliar pada 2022 dan naik menjadi Rp450,2 miliar pada 2023. Namun hingga kini, tak satu pun lembaga negara memverifikasi legalitas lahan sumber bahan baku tersebut. Pemerintah lebih sibuk memuji “kemandirian energi” ketimbang menegakkan hukum di sektor yang penuh konflik ini. Padahal, prinsip due diligence dalam perdagangan hasil sawit mengharuskan setiap rantai pasok bebas dari pelanggaran hukum.
Ironinya, proyek biodiesel senilai Rp2 triliun yang diresmikan langsung Presiden Jokowi pada 2021 justru menyisakan noda hukum. Energi hijau yang digembar-gemborkan ternyata dibangun di atas pelanggaran pidana: dari kriminalisasi warga, tumpang tindih izin, hingga potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pulau Laut pun menjadi saksi betapa hukum bisa lentur di hadapan modal, tapi keras terhadap rakyat kecil. Ketika energi disebut “hijau”, warna keadilan justru menjadi kelabu. []
Redaksi