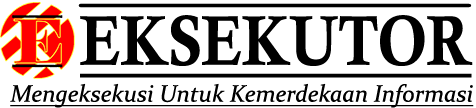KUPANG — Dugaan salah tuduh terhadap seorang siswa sekolah dasar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memunculkan keprihatinan publik terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Seorang siswa kelas III SD Negeri Oehendak, Kecamatan Maulafa, berinisial YA (9), mengalami tekanan psikologis berat setelah dituding mencuri telepon genggam milik penjaga sekolah. Peristiwa tersebut berdampak serius terhadap kondisi mental anak, hingga membuatnya enggan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Kasus ini disampaikan langsung oleh ibu kandung YA, Gaudensia Eko (37), yang menuturkan bahwa tuduhan tersebut membuat anaknya merasa tertekan, malu, dan takut. Menurut penuturan keluarga, peristiwa bermula pada Senin, 2 Februari 2026, sekitar pukul 12.00 Wita, ketika sebuah telepon genggam milik penjaga sekolah diletakkan di atas meja di lingkungan sekolah.
Dalam situasi tersebut, YA sempat mengambil ponsel tersebut dan menyimpannya di dalam laci meja sebelum kembali mengikuti pelajaran di kelas. Setelah itu, YA pulang seperti biasa dan tidak mengetahui bahwa ponsel tersebut kemudian dinyatakan hilang. Dua hari kemudian, pihak sekolah menghubungi keluarga dan meminta orangtua YA datang ke sekolah.
Pemanggilan tersebut berdampak langsung pada kondisi psikologis anak. “Dia bangun malam sambil menangis dan bilang, Mama bukan saya curi, saya hanya ambil dan taruh di laci,” tutur Gaudensia.
Keesokan harinya, Gaudensia dan anaknya mendatangi sekolah. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyatakan YA sebagai pihak yang mengambil ponsel dengan dasar adanya saksi yang melihat peristiwa tersebut. Gaudensia menjelaskan bahwa anaknya memang sempat mengambil ponsel itu, namun tidak membawanya pulang dan tidak menyimpannya di dalam tas.
“Saya jelaskan, anak saya memang ambil, tapi tidak bawa pulang dan tidak simpan di tas. Kalau mencuri, pasti dibawa,” kata Gaudensia.
Namun, keluarga menilai bahwa posisi YA seolah dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas hilangnya barang tersebut. Tekanan tidak hanya dirasakan anak, tetapi juga berdampak pada kondisi emosional orangtua. Dalam ketakutan akan kemungkinan persoalan hukum, Gaudensia mengaku sempat melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya karena khawatir YA berbohong.
“Saya orang kecil, jual sayur sehari cuma dapat Rp 5.000. Saya takut anak saya masuk penjara,” ujarnya sambil menangis.
Keluarga sempat meminta agar kasus ini dilaporkan ke kepolisian untuk mengungkap kebenaran secara objektif. “Kalau tidak mau lapor polisi, berarti ada yang ditutupi,” ujar Gaudensia. Namun, usulan tersebut ditolak pihak sekolah dengan alasan menjaga nama baik institusi.
Pihak sekolah kemudian memberikan tenggat waktu dua minggu kepada keluarga untuk mencari ponsel tersebut. Selama periode itu, YA tidak masuk sekolah karena merasa takut dan malu. Tekanan psikologis semakin berat karena tidak adanya kepastian dan klarifikasi yang jelas.
Fakta baru terungkap ketika pihak sekolah menyampaikan bahwa ponsel tersebut telah ditemukan. Barang itu ternyata diambil oleh seorang siswa SMP Negeri 13 Kupang yang menitipkannya di sebuah kios untuk ditukar dengan makanan ringan. Informasi tersebut membuat keluarga terpukul, sekaligus menyesal atas perlakuan yang telah dialami anak mereka.
“Anak saya tidak mencuri. Tapi dia sudah terlanjur trauma,” kata Gaudensia.
Meski demikian, pihak sekolah disebut tidak bersedia menyampaikan klarifikasi terbuka bahwa YA tidak bersalah. Permintaan orangtua agar dilakukan klarifikasi di hadapan kelas dan menghadirkan siswa SMP yang mengambil ponsel tersebut juga tidak dikabulkan. Bahkan, Gaudensia mengaku mendapat perlakuan yang tidak pantas saat menyampaikan keberatan.
“Guru-guru tertawa. Kepala sekolah bilang saya tidak boleh atur sekolah,” ucapnya dengan suara bergetar.
Hingga kini, YA belum kembali bersekolah meski sudah memasuki masa ujian. Orangtua khawatir trauma psikologis yang dialami anaknya akan berdampak jangka panjang, termasuk risiko perundungan dan gangguan mental. Keluarga menegaskan hanya menginginkan pemulihan nama baik dan kondisi psikologis anak.
“Saya cuma minta satu, umumkan bahwa anak saya tidak mencuri. Jangan korbankan anak kecil demi nama sekolah,” tegas Gaudensia.
Ia menyatakan siap menempuh jalur pengaduan hingga ke tingkat pemerintah provinsi demi mendapatkan keadilan bagi anaknya. “Kami memang miskin, tapi kami punya harga diri,” pungkasnya. []
Diyan Febriana Citra.