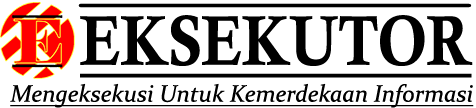BANDUNG – Kasus pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP di Kabupaten Bandung Barat membuka kembali diskusi publik mengenai pentingnya kesehatan mental dan pendampingan emosional pada usia remaja. Peristiwa tragis yang menewaskan ZAAQ (12) dan melibatkan dua remaja lain, YA (16) dan AP (17), menunjukkan bahwa konflik relasi pertemanan di usia belia dapat berkembang menjadi persoalan serius apabila tidak dikelola secara sehat.
Psikolog dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Miryam Ariadne Sigarlaki, menilai bahwa penolakan dalam pertemanan memiliki dampak psikologis yang jauh lebih dalam bagi remaja dibandingkan orang dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan fase pencarian jati diri yang sedang dialami anak-anak pada usia tersebut.
“Yang bisa kita pegang ini dari fakta hukum yang sudah disampaikan kepolisian jadi hanya sebatas hipotesa umum,” ungkap Miryam saat dihubungi, Selasa (17/02/2026).
Berdasarkan keterangan penyidik, YA diduga telah merencanakan aksinya dengan membawa pisau dari Garut ke Bandung setelah merasa kecewa karena hubungannya dengan korban diputus. Fakta ini memperlihatkan bagaimana emosi negatif yang tidak tersalurkan dapat berkembang menjadi tindakan ekstrem.
Dalam kajian psikologi, Miryam menjelaskan bahwa perasaan malu, marah, dan terhina akibat penolakan sosial dapat menjadi luka batin yang berbahaya jika terus dipelihara.
“Dalam psikologi, putus pertemanan ini bisa saja memicu luka secara psikologis. Malu, kemudian marah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Miryam menyebutkan bahwa kondisi tersebut sering diperparah oleh ruminasi, yakni pola pikir berulang yang terus-menerus memutar pengalaman negatif di dalam benak pelaku.
“Pada sebagian remaja, emosi itu bisa menguat jika ada pikiran yang berulang-ulang. Rasa yang dipermalukan dengan pikiran-pikiran buruk yang menguatkan perasaan itu,” lanjut Miryam.
Akumulasi emosi tersebut dapat menurunkan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri dan menilai situasi secara rasional. Dalam fase ini, muncul krisis identitas yang membuat pelaku melihat dunia secara hitam-putih dan membenarkan kekerasan sebagai jalan keluar.
“Dari ruminasi itu, kemudian pikirannya membenarkan tindak kekerasan, ‘Dia pantas mati. Kalau tidak aku semakin dipermalukan’. Ini menurunkan kendali rem moral kita,” tutur Miryam.
Namun demikian, Miryam menegaskan bahwa tindak kekerasan tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal. Selain lemahnya regulasi emosi secara internal, faktor situasional seperti kesempatan bertemu di lokasi sepi dan akses terhadap senjata tajam turut memperbesar risiko terjadinya kejahatan.
“Kalau orang marah itu nular, jadi ketika semua situasional itu atmosfernya marah itu akan jadi satu peluang. Sehingga paparan kekerasan ini bisa terjadi,” katanya.
Dari sisi pencegahan, Miryam menilai pendekatan represif semata tidak cukup. Ia menekankan pentingnya peran orangtua dan sekolah dalam membangun keterampilan sosioemosional anak sejak dini.
“Kuncinya, sekolah dan orangtua perlu memperkuat keterampilan sosioemosional pada anak anak. Kita bisa fokus pada pencegahan, bukan menghakimi,” kata Miryam.
Ia juga mengingatkan agar perubahan perilaku remaja yang mencolok, seperti munculnya obsesi balas dendam, penarikan diri ekstrem, atau ancaman kekerasan, tidak diabaikan.
“Kalau ada remaja yang menunjukan ancaman kekerasan, obsesi balas dendam yang inginnya dendam atau perubahan perilaku drstis, saran saya libatkan pihak sekolah, orangtua, atau kalau bisa layanan psikologis terdekat,” jelas Miryam.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental remaja adalah tanggung jawab bersama, yang memerlukan keterlibatan keluarga, institusi pendidikan, serta lingkungan sosial untuk mencegah tragedi serupa terulang. []
Diyan Febriana Citra.